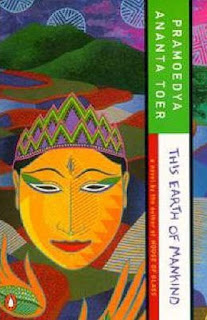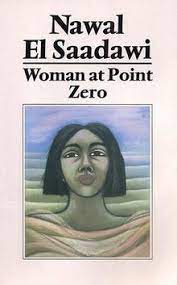Syahdan, atau tepatnya sejarah mencatat, pada tanggal 22 Desember 1928, tak lama setelah Kongres Sumpah pemuda, sebuah Kongres Perkoempoelan Perempoean Indonesia diadakan.
Ini adalah titik awal perjuangan perempuan yang diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari daerah-daerah di Indonesia, di antaranya adalah Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika dan Wanita Taman Siswa.
Pembahasannya? Hak-hak perempuan dalam dunia pendidikan, pernikahan, hukum, serta peranannya dalam negara.
Dengan pesan tersebut, Presiden Soekarno meresmikannya menjadi “Hari Ibu”, sebagai pengingat kesadaran berbangsa dan bernegara pada perempuan.
Secara perlahan, di masa Orde Baru, warna dan makna Hari Ibu terdomestikasi menjadi perayaan pada perempuan yang punya anak, yang tugasnya merawat keturunan dan mengabdi pada suami.
Maka tak heran jika kita terbiasa melihat ucapan hari Ibu hadir dengan gambar seorang perempuan dengan si anak dalam buaian, atau disisi. Tak jarang ada ilustrasi sapu, penggorengan, serta si anak dalam gendongan. Ibu adalah yang punya anak. Titik.
Lebih jauh lagi, berbagai perusahaan retail hadir dengan curahan potongan belanja bagi kaum Ibu, perawatan spa dengan harga miring diberikan bagi Ibu yang ternyata banyak yang tak sempat merawat diri atau sekedar pakai gincu.
"Terima kasih sudah melahirkanku, memasak buatku, membesarkanku." Begitu rata-rata yang tertulis di kartu.
Apakah ini salah? Tidak. (If you’re sensing a “but” coming in, you are right)
Tetapi…
Akankah lebih baik jika kita kembali memaknai Hari Ibu seperti dicanangkannya dulu? Saat perempuan paham betul bahwa peranannya bisa beragam dan semuanya layak dimeriahkan?
Ketika perempuan memberdayakan diri sebagai bukan hanya yang membesarkan keturunannya, sekaligus juga bisa berperan aktif dalam soal ekonomi, politik, dan mendidik generasi bangsa?
Kasus pemerkosaan, pelecehan, kekerasan, dan (drumroll please) RUU PKS yang tak kunjung jadi kenyataan…. Bukankah seharusnya mendapatkan porsi besar untuk disuarakan juga di Hari Ibu?
Pengetahuan menyoal consensual sex, pengupahan setara, hak-hak dan akses mendapatkan alat kontrasepsi serta fasilitas kesehatan, bukankah akan lantang terdengar jika kita titipkan di sela-sela ucapan Hari Ibu?
Seperti Hari Kartini yang sering salah kaprah dirayakan dengan lomba masak pakai sepatu hak tinggi dan kebaya, Hari Ibu, seperti punya wajah yang terlalu monochromatic, tetapi dengan suara yang teredam. Diam.
Untuk catatan, pelajaran ini, pertama saya dapatkan dari seorang Ibu beranak empat, yang selalu membalas dengan “Ini hari untuk semua perempuan. Bukan buat Mama saja.” Saat anak-anaknya mengucapkan.
Terima kasih Tante Yanti, ilmu ini adalah salah satu amal ibadahmu, yang kudoakan semoga Tuhan perhitungkan si surga sana.
Selamat Hari Ibu, Perempuan Indonesia.
Yang Ibu rumah tangga, yang bekerja di kantor. Yang berusaha punya keturunan, pun yang tak punya mau. Yang menikah, dan yang urung.
Yang guru, yang dokter, yang memakai helm di proyek-proyek atau yang terbakar matahari di pekerjaannya.
Selamat Hari Ibu, Perempuan Indonesia.
Yang merintis usaha rumahan, yang duduk di kursi jabatan tinggi, yang berjuang di jalur keras bagi korban ketidakadilan, yang masih di hutan belantara memperjuangkan sepenggal lahan hutan untuk ciptaan Tuhan lainnya selain manusia.
Terima kasih, karena cerita-cerita kita yang berbeda ini, sungguh sangat menguatkan hati.
Hari ini, untuk kita.
Foto dari wikipedia